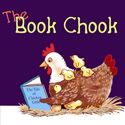Tahun 1991. Saya dan teman berjalan pulang dari sekolah di bawah terik matahari pukul sebelas. Kami berjalan kurang lebih dua kilometer. Saya masih kelas satu SD saat itu. Sebelumnya, guru bertanya tentang cita-cita kami. Di antara semua teman, saya nyaris tidak sempat menjawab. Ada banyak tangan yang mengacung dan berebut menjawab. "Dokter!" "Pilot!" "Bos!" dan sebagainya. Saya, si pemikir, ternyata terlalu lama berpikir. Di sepanjang perjalanan pulang itu saya terus berpikir, dan akhirnya teman seperjalanan saya bertanya. "Kau mau jadi apa?"
"Hari senin aku akan menjadi dokter. Hari rabu aku jadi polisi (waktu itu saya takjub pada Robocop). Hari berikutnya aku akan jadi istri Superman (waktu itu superman=Dean Cain)."
Teman saya melihat saya dengan tatapan kalau saya sudah gila.
Saya memang terlahir dengan banyak cita-cita. Ingin menjadi segalanya. Ketika ditanya Bapak (almarhum) saya akan menjawab "bankir" biar beliau senang. Ketika ditanya ibu, saya menjawab "dokter" juga agar beliau senang.
Makin kemari ternyata cita-cita saya tidak mengerucut. Tetap saja masih banyak. Tapi saya lama-lama sadar, ada beberapa hal yang tidak bisa saya kuasai meskipun saya ingin. Mungkin bisa, tapi kemudian saya sadar bahwa kita harus berbagi peran. Keinginan saya untuk menjadi segalanya mungkin secara tidak sadar berawal dari ketidakpercayaan saya pada orang lain. Atau karena saya terlalu ingin menyenangkan ibu bapak saya. Begitu saya bisa memercayai orang bisa melakukannya dengan baik, saya merasa tidak perlu mengerjakan hal itu. Dulu saya berpikir (maafkan pikiran sok anak umur 5 thn ini) kalau dunia akan beres (waktu itu Bosnia lagi perang) kalau saya mengerjakan semuanya.
Ketika beranjak dewasa, saya menyadari hal lain lagi. Kita sering mendengar kalimat, "gantungkan cita-citamu setinggi langit." Tapi saya lupa diberitahu bahwa langit itu milik bersama. Cita-cita satu orang akan memengaruhi cita-cita orang lain. Saya pun berpikir, betapa egoisnya saya selama ini, mengumumkan cita-cita saya tanpa mempertimbangkan, bintang yang saya gantung di langit itu akan bersinggungan dengan bintang siapa?
Saya memiliki seorang teman, namanya Mai. Suatu hari ia datang ke kamar saya--waktu saya hampir lulus SMU. Ia berkata bahwa tidak bisa kuliah. Karena tahun depan adiknya akan kuliah juga di jurusan yang sama. Ayahnya meminta dia untuk segera bekerja, dan membantu membiayai kuliah adiknya, atau setidaknya menafkahi dirinya sendiri.
Saya berduka untuk Mai. Ia bahkan tak bisa menggantung bintang di langit cita-citanya, karena bagi keluarganya, langit itu sangat sempit dan mereka harus berbagi. Lalu saya teringat kakak saya yang masuk militer. Apakah dia mengganti cita-citanya--dia adalah penulis dan kartunis yang hebat-- agar saya bisa menggantung cita-cita lebih tinggi? Ah... andai saya tahu.
Saya masih belum dewasa juga, ketika akhirnya saya menikah. Dan perkara cita-cita ini bertambah pelik. Suatu hari tanpa sengaja saya mendengar obrolan di radio, antara seorang penelepon dengan psikolog. Penelepon itu bertanya, "Saya diterima kuliah di Jerman, tapi suami dan anak saya tidak bisa ikut, bagaimana saya harus memutuskannya?" psikolog itu menjawab,
"itu adalah pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan sebelum melamar pekerjaan atau beasiswa. Sekarang, Anda harus memilih dengan resiko yang cukup ekstrim. Meninggalkan salah satunya." --jangan bahas jawaban psikolog tega ini, sepertinya dia capek atau bagaimana--
"itu adalah pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan sebelum melamar pekerjaan atau beasiswa. Sekarang, Anda harus memilih dengan resiko yang cukup ekstrim. Meninggalkan salah satunya." --jangan bahas jawaban psikolog tega ini, sepertinya dia capek atau bagaimana--
Saya merenung. Setiap keputusan, bahkan yang menyangkut hal yang paling kita inginkan... kini harus diambil bersama setelah seseorang menikah. Karena keputusannya akan memengaruhi orang lain di sisinya.
Setelah punya anak, saya jarang memikirkan cita-cita saya pribadi. Ketika ditanya punya target apa, otomatis otak saya akan memindai target-target pertumbuhan anak saya. Sekolah mana yang cocok, kurikulum apa yang diperlukan, metode apa yang kami setujui. Baru beberapa saat kemudian saya akan sadar, "oh, target saya?"
"Nggak ingin sekolah S2 lagi, Mbak?" tanya seorang teman.
Tentu. Meski bukan kata 'S2' yang dicerna oleh benak saya, melainkan kata 'sekolah'. Mungkin mengulang S1 dengan jurusan yang berbeda. Mungkin sekedar short course terkait pekerjaan saya. Tidak penting. Asal itu adalah judul dari menuntut ilmu.
"Tidak mau mengajukan aplikasi beasiswa?"
Untuk saat ini tidak. Tidak memungkinkan bagi saya untuk meninggalkan anak-anak. Membawa mereka? Dan menjadi beban orang lain? Saya berpikir tentang mereka yang masih single dan benar-benar membutuhkan pendidikan lanjutan. Sementara saya, saya tidak sekepepet itu untuk harus mengambil S2. Untuk kebutuhan saya, masih banyak pendidikan di dalam negeri yang terjangkau. Tidak tahu kalau besok-besok.
"Kasihan, sudah sarjana cuma di rumah." Saya tertawa pada kalimat ini. Tak masalah bagi saya. Saya juga tidak merasa harus membela diri. Kenapa?
Mm... saya justru bertanya, untuk apa saya membela diri?
Saya tahu saya ada di titik mana dalam hidup dan akan ke mana melangkah. Jadi kenapa saya harus menjelaskan pada orang yang tidak menjalaninya.
Mm... saya justru bertanya, untuk apa saya membela diri?
Saya tahu saya ada di titik mana dalam hidup dan akan ke mana melangkah. Jadi kenapa saya harus menjelaskan pada orang yang tidak menjalaninya.
Sekarang, anak-anak sudah mau masuk sekolah. Saya akan menjadi ibu kesepian di jendela. Sedih rasanya membayangkan rumah sepi tanpa teriakan mereka. Kosong, tidak lagi meneriaki mereka dari jendela, "Heeey, itu kotoran ayaaam!"
Tapi mereka bertumbuh. Saya harap ilmu dan amal saya pun akan bertumbuh. Karena itu, meski rasanya sesak, saya mulai mencari-cari sekolah dan pekerjaan untuk diri saya sendiri. Secukupnya, yang tidak perlu merenggut saya dari rumah. Mungkin sekedar menghabiskan waktu selama anak-anak di luar.
"Apa kamu punya cita-cita?" tanya seseorang, melihat saya yang katanya tidak memiliki ambisi. Saya tersenyum. Saya punya. Tak perlu saya sebutkan.
Ia ada dalam doa. Di antara bisikan agar Allah menjernihkan hati saya, membedakan antara cita-cita dan nafsu mengejar citra: wanita berpendidikan tinggi.
Ia ada dalam doa. Di antara bisikan agar Allah menjernihkan hati saya, membedakan antara cita-cita dan nafsu mengejar citra: wanita berpendidikan tinggi.
Bagi saya, cita-cita adalah yang digenggam dalam diam, diupayakan selangkah demi selangkah, tetap gigih meski tak ada yang mengetahui ia menginginkannya. Tak iri melihat orang lebih duluan mencapai cita-citanya. Tak lemah melihat tak ada yang menyemangatinya. Tak tergempur oleh arus. Tak berkarat oleh sorak-sorai. Ia teguh sejak dalam hati. Berusaha dan berusaha....
Saya meyakini, Allah akan mendekatkan apa yang diam-diam kita idamkan, jika kita bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diamanahkan sekarang.