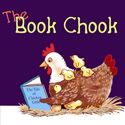Seolah hanya sekedip mata, tiba-tiba kita sudah menjadi orangtua. Rasanya baru kemarin kita mendengarkan nasihat dan kasih sayang dari ayah ibu kita. Lalu hari ini, sebuah jiwa telah memanggil kita sebagai ayah, atau ibu. Begitu cepat, hampir-hampir tak dipersiapkan. Kadangkala saya menemukan ilmu setelah terlanjur mengalami, bukan sebaliknya. Ah, kasihan anak-anak. Kalau saja saya lebih dulu belajar, mereka tidak perlu terlanjur menjadi korban ketidaksiapan.
Tapi, begitulah menjadi orangtua. Proses tak berkesudahan. Pembelajaran dari hari ke hari. Seperti yang dikatakan orang, ketika kita menjadi orangtua, bukan saja anak yang belajar dari kita, melainkan kita belajar tentang hidup dari mereka.
Ada banyak sekali nasihat-nasihat parenting untuk ayah dan ibu. Dari berbagai sudut pandang. Akhirnya saya paham, tidak ada yang salah dan benar dalam metode tersebut. Hanya mengenai ingin menjadi orangtua yang bagaimanakah kita.
Misalnya...
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa usia terbaik belajar teknologi adalah 3 tahun. Penelitian lain menyebutkan, anak-anak perlu bermain dan belajar di luar. Tak baik membiarkan mereka terpapar screen terlalu dini. Keduanya benar. Tergantung Anda, ingin menjadikannya penjelajah alam, atau penjelajah cyber.
Contoh lain,
Suatu hari koran Tempo di Indonesia memuat artikel tentang bahayanya anak menonton TV terlalu lama. Lucunya, di hari yang sama BBC mengeluarkan artikel tentang penelitian bahwa menonton televisi tidak membuat anak bodoh atau otaknya mampet seperti yang dikira orang. TV membuat anak mendapatkan nilai rendah karena mereka menggunakan waktu mengerjakan PR nya untuk menonton televisi.
Mana yang benar? Saya melihat pada anak-anak saya. Semuanya tergantung bagaimana anda, sebagai orangtua, memantau kegiatan anak. Dari TV ia bisa melihat banyak hal: tergantung channelnya. TV membuat anak konsumtif: kalau anda menuruti semua yang dia minta. TV membuat anak gemuk: kalau anda biarkan ia makan di depan TV. TV menjadi berguna ketika kita memantau tayangan dan durasinya. Kitalah bossnya, bukan televisi.
Tidak usah berdebat dan tersinggung dengan metode orangtua lain membesarkan anaknya. Seorang teman memasukkan anaknya ke Islamic School sedini mungkin, karena ia berharap anaknya menjadi hafidz, dan ilmuwan dalam dunia Islam. Anda yang ngeri melihat bagaimana anak kecil harus menghafal begitu banyak, tidak usah mengernyit. Pada dasarnya kemampuan intelektual anak akan menyanggupi hal tersebut. Mentalnya? nah, itu adalah pekerjaan orangtua. Kalau anaknya diinginkan menjadi hafidz, maka orangtuanya harus menyiapkan mental yang kuat, sehingga anak tidak sekedar menjadi penghafal, namun pecinta Al Quran.
Ada orangtua yang ingin anaknya menjadi pionir. Ia menggemblengnya sedemikian rupa sejak dini.
Ada orangtua yang ingin anaknya menjadi pembawa ketenangan dunia. Dunia sudah cukup tertekan, ia ingin anaknya tumbuh sebagai jiwa tenang yang bergembira.
Ada orangtua yang ingin anaknya disiplin sejak bayi. Karena ia mengira dunia tempatnya hidup penuh dengan kompetisi.
Ada orangtua yang cukup bahagia jika anaknya berhasil menanam bulir-bulir jagung di pekarangan.
Dunia membutuhkan ulama, ilmuwan, petani, nelayan, dokter, guru, seniman, penulis, dan tentara.
Anak kita akan menjadi salah satunya. Ringankan diri dari tugas mengkritik cara orangtua membesarkan anak mereka. Karena anak kita dengan anaknya jelas berbeda. Mereka sudah diberi Allah bakat masing-masing, orangtua hanya perlu melihatnya dengan hati dan menempanya dengan hati-hati, agar ia tidak rusak. agar bakat tidak menjadi sumber bencana: stress, terlalu kompetitif, hipersensitif, dan kerapuhan jiwa lainnya.
Apakah kita masih membutuhkan segala teori parenting itu?
"bacalah anakmu, bukan buku," begitu pepatah Afrika berbunyi.
Kita masih memerlukan buku, panduan, teman, untuk mengetahui bahwa kita tidak keluar dari garis. Namun semua itu tidak untuk mendikte kita untuk memangkas anak menjadi seperti yang kita, atau dunia, inginkan. Anak memiliki jalannya sendiri. Kita hanya perlu menggandengnya dengan selamat.
Tahun lalu, saya masih bisa tertawa ketika membicarakan pilihan sekolah untuk anak. Waktu itu saya sedang menulis artikel untuk koran lokal. Tanpa kecurigaan saya berhasil melist beberapa sekolah bagus. Tahun ini, ketika putri saya siap menginjakkan kakinya di Taman Kanak-Kanak, saya tidak bisa tertawa lagi. Ini masalah serius. Sekolah-sekolah yang ada di list saya tahun lalu, mulai saya tatap dengan pandangan skeptis.
Kalau ada teman yang memuji sekolah anaknya, saya pasti langsung cara tahu, di mana??
Waktu masih tinggal di Jogja, saya sudah mencoret-coret kriteria sekolah untuk anak saya bahkan waktu dia masih dalam perut. Saya bakan nanya ke Bambini, kira-kira per tahun biaya sekolahnya naik berapa persen--berkaitan dengan tabungan dan sebagainya-- dan kalau-kalau anda mau tau, jawabannya adalah 20 % kenaikan setiap tahun. Bagooss...
Sayangnya di Kota ini saya tidak punya banyak pilihan. Montessori yang Islami, ada nggak? :D
Sejauh ini saya berhasil menahan anak-anak untuk belajar dari rumah. Ya ampun, belajar... main-main doang aslinya. Main masak-masak, susun-susun, cari harta karun, nonton Dora, main playdough, dll.... Sejauh ini anak saya masih terbalik balik menghitung 1-10. So what? Setidaknya dia sudah bisa membuka pintu dan menginterogasi tamu. Di dunia yang beringas ini (kalau nenek saya masih hidup, dia pasti kaget lihat dunia skarang) keterampilan menghadapi orang lebih saya hargai daripada menghitung 1-10 (karena toh pada akhirnya dia akan hafal. Lihat saja saya, memangnya umur berapa saya bisa berhitung, nggak ngefek juga ke kehidupan saat ini)--oh well, saya mendengar beberapa orang berkata: kalau kamu lebih cepat belajar berghitung, siapa tau kamu sudah bekerja di NASA saat ini :p
Tapi, demi satu dan lain hal, saya harus mencarikan sekolah yang tepat untuk anak saya. Nah, kata tepat itu yang nggak mudah.
Ada sebuah sekolah keren. SDIT. Pertama, jauhnya minta ampun. Baiklah, sekolah memang butuh pengorbanan, tapi kalau tenaga dan waktunya harus habis di perjalanan? Apalagi yang tersisa untuk di rumah? padahal dunia yang harus dieksplorasinya bukan cuma sesempit lapangan sekolah.
Kedua, mahal. Beruntunglah anda-anda yang berhaisl menemukan sekolah relijius yang jarak dan biayanya terjangkau. Saya nggak akan belagu dengan bilang kalau saya bukan pendukung komersialisasi SDIT, masalah saya adalah ini terlalu mahal dan nggak sesuai dengan budget saya. Kalau menurut anda saya harus berkorban, menabung, dan berasuransi, tengkyuverymuch, katakan itu pada tujuh puluh persen penduduk negeri ini yang kebutuhannya bukan cuma membiayai kaca anti peluru sekolahnya atau biaya perawatan rumput bermuda di halaman sekolah.
Kenapa harus sekolah relijius? Padahal di sekolah seperti itu anak-anak akan didoktrin, diharuskan menghafal...blablabla... "alim aja bisa korupsi" kata seorang teman. Rrr... itu dia, yang alim aja bisa khilaf, apalagi yang buta? Saya berharap anak-anak punya pegangan, masalah apakah pegangannya kuat dan selamanya, tentu bukan perkara sekedar membalik tangan. Orang tua dan pendidik di sekolah harus sama-sama menginstal jiwa-jiwa yang kuat itu pada anak-anak. Well, akan banyak kritik, apa sih yang dikritik orang saat ini. But for me, jawabannya cuma satu kata: aqidah. tidak bisa didebat lagi.
Soal aqidah tidak bisa diganggu gugat, yang lain masih bisa dinego. Dulu, daftar saya panjaaang sekali. Akhir-akhir ini saya mulai insaf.
Ini daftar insaf saya:
1. Tidak ada sekolah yang sempurna untuk melepaskan anak anda. Tapi ada banyak yang cukup baik untuk anda jadikan partner mendidik anak. ingat ya, partner, jadi jangan lepas tangan.
2. Sekolah bukanlah semesta pendidikan. Sekolah hanya sebuah tempat. Sebuah rantai dari serangkaian upaya untuk mengajarkan anak melihat dunia. Jadi saya tidak bisa menganggap urusan pendidikan anak selesai dengan memberinya sekolah, tak peduli bagaimana rating sekolah itu. Bagus atau tidak sekolah, kami tetap masih harus mendidiknya di rumah.
3. Kadang-kadang saya pikir, urusan mencari sekolah yang baik ini, apakah benar-benar karena saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, atau karena saya tidak ingin mereka kalah dibandingkan anak-anak lain? Karena kalau saya benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak saya semata, maka seharusnya saya mengukur kredibilitas sekolah itu dari sudut pandang anak saya. Apakah itu tempat yang nyaman, apakah toiletnya tidak ketinggian, apakah guru itu tidak galak, apakah sekolah itu mengerti tentang beberapa keterbatasannya dan mengapresiasi dengan tulus beberapa kelebihannya?
4. Saya bertemu seorang ibu dari generasi di atas saya. Tinggal di desa, dengan sekolah negeri yang gaji gurunya pas-pasan, fasilitas terbatas, namun anak-anaknya berhasil tumbuh dewasa sebagai pribadi yang hebat? Dikasih apa Buuu?
"Sekolah itu tempat dia mendengar, melihat. Rumah itu tempat dia menyaring mana yang harus diterimanya, mana yang harus diabaikan."
Sang ibu menyediakan waktunya (sudah belasan tahun,kalau dihitung-hitung) untuk mendengarkan anak-anaknya. Obrolan seperti, tadi di sekolah belajar apa, temanmu kenapa, siapa yang terluka, siapa yang merusak apa, apa yang kalian lakukan ketika dihukum...
5. Tidak ada guru yang sempurna. Tentu saja, guru sesekali marah dengan yang berkecenderungan psikopat tentu berbeda. Saya mengenal seorang guru yang selalu mencaci-caci di wall facebooknya, memaki anak didiknya (meski di belakang) dan mengaku telah mematahkan penggaris di pantat muridnya. Saya berdoa cukup dia saja guru yang punya kelabilan jiwa seperti itu. Aamiin. Tapi, saya cukup tenang membaca nasihat Marie Hartwell--psikolog dan konsultan pendidikan untuk orang tua-- bahwa, guru bukanlah malaikat. Dia punya tekanan, masalah rumah, masalah sekolah, tuntutan orang tua dan kepala sekolah.. ketika suatu hari anda menemukan ia marah, jangan buru-buru memakinya balik dan mengeluarkan anak anda dari sekolah. Ajak ia bicara. siapa tau kepala dingin anda bisa menular padanya ;)
6. Dan, saya menemukan sekolah itu. TK negeri yang mungil, dengan halaman hijau dan pohon-pohon teduh. Ada banyak yang mengkritik, oke, bertanya, kenapa dan berapa. Bagi saya ini mencukupi. Semuanya bisa diatur, saya hanya perlu menginstal jiwa pembelajar dalam diri saya dan anak-anak. Kekurangan yang akan kami temui, akan kami bicarakan, akan kami perbaiki. Sebisanya. Kata seorang teman generasi tua: hadiahkan guru anakmu sebuah buku, atau sebuah obrolan dari hati ke hati....
Tentu saya khawatir pada efek kekerasan--apapun bentuknya-- termasuk tindakan bullying. Di negeri ini, drama komedi saja isinya mbully. Tapi, saya sendiri menghabiskan dua pertiga masa SD saya dengan menjadi korban bully sesama teman. Separo masa SMP saya dibully oleh guru. Masa SMU saya sepenuhnya dibully oleh sistem. Dan sebagian besar teman-teman saya merasakan hal yang sama. Kekerasan pada masa itu dianggap tindakan wajar, pendisiplinan. Tapi saya baik-baik saja, thank to my mother. Dan buku-buku serta kepercayaan diri yang diwariskan ayah saya.
Di masa ini, bukan berarti saya akan memaklumi tindak kekerasan di sekolah. Tapi saya akan kehilangan waktu dan banyak kesempatan jika hanya fokus menghindari. Kalaupun saya dan anak-anak bisa menghindari, tidakkah sebagai ibu cukup untuk membuat saya mempertimbangkan kecemasan ibu lain yang anaknya harus masuk ke sekolah negeri dengan banyak keterbatasan, sementara mereka tidak punya banyak pilihan. Saya mungkin bisa berlega untuk anak-anak saya, tp bagaimana dengan anak lain? Karena itu, saya memilih menerima ketidaksempurnaan, tidak menghindarinya mati-matian sampai kategori alergi sekolah miskin, dan bersama ibu-ibu lain, saya harap kami bisa memperbaikinya (cita-cita itu harus muluk, biar rajin mencapainya :))
Kalau ada teman yang memuji sekolah anaknya, saya pasti langsung cara tahu, di mana??
Waktu masih tinggal di Jogja, saya sudah mencoret-coret kriteria sekolah untuk anak saya bahkan waktu dia masih dalam perut. Saya bakan nanya ke Bambini, kira-kira per tahun biaya sekolahnya naik berapa persen--berkaitan dengan tabungan dan sebagainya-- dan kalau-kalau anda mau tau, jawabannya adalah 20 % kenaikan setiap tahun. Bagooss...
Sayangnya di Kota ini saya tidak punya banyak pilihan. Montessori yang Islami, ada nggak? :D
Sejauh ini saya berhasil menahan anak-anak untuk belajar dari rumah. Ya ampun, belajar... main-main doang aslinya. Main masak-masak, susun-susun, cari harta karun, nonton Dora, main playdough, dll.... Sejauh ini anak saya masih terbalik balik menghitung 1-10. So what? Setidaknya dia sudah bisa membuka pintu dan menginterogasi tamu. Di dunia yang beringas ini (kalau nenek saya masih hidup, dia pasti kaget lihat dunia skarang) keterampilan menghadapi orang lebih saya hargai daripada menghitung 1-10 (karena toh pada akhirnya dia akan hafal. Lihat saja saya, memangnya umur berapa saya bisa berhitung, nggak ngefek juga ke kehidupan saat ini)--oh well, saya mendengar beberapa orang berkata: kalau kamu lebih cepat belajar berghitung, siapa tau kamu sudah bekerja di NASA saat ini :p
Tapi, demi satu dan lain hal, saya harus mencarikan sekolah yang tepat untuk anak saya. Nah, kata tepat itu yang nggak mudah.
Ada sebuah sekolah keren. SDIT. Pertama, jauhnya minta ampun. Baiklah, sekolah memang butuh pengorbanan, tapi kalau tenaga dan waktunya harus habis di perjalanan? Apalagi yang tersisa untuk di rumah? padahal dunia yang harus dieksplorasinya bukan cuma sesempit lapangan sekolah.
Kedua, mahal. Beruntunglah anda-anda yang berhaisl menemukan sekolah relijius yang jarak dan biayanya terjangkau. Saya nggak akan belagu dengan bilang kalau saya bukan pendukung komersialisasi SDIT, masalah saya adalah ini terlalu mahal dan nggak sesuai dengan budget saya. Kalau menurut anda saya harus berkorban, menabung, dan berasuransi, tengkyuverymuch, katakan itu pada tujuh puluh persen penduduk negeri ini yang kebutuhannya bukan cuma membiayai kaca anti peluru sekolahnya atau biaya perawatan rumput bermuda di halaman sekolah.
Kenapa harus sekolah relijius? Padahal di sekolah seperti itu anak-anak akan didoktrin, diharuskan menghafal...blablabla... "alim aja bisa korupsi" kata seorang teman. Rrr... itu dia, yang alim aja bisa khilaf, apalagi yang buta? Saya berharap anak-anak punya pegangan, masalah apakah pegangannya kuat dan selamanya, tentu bukan perkara sekedar membalik tangan. Orang tua dan pendidik di sekolah harus sama-sama menginstal jiwa-jiwa yang kuat itu pada anak-anak. Well, akan banyak kritik, apa sih yang dikritik orang saat ini. But for me, jawabannya cuma satu kata: aqidah. tidak bisa didebat lagi.
Soal aqidah tidak bisa diganggu gugat, yang lain masih bisa dinego. Dulu, daftar saya panjaaang sekali. Akhir-akhir ini saya mulai insaf.
Ini daftar insaf saya:
1. Tidak ada sekolah yang sempurna untuk melepaskan anak anda. Tapi ada banyak yang cukup baik untuk anda jadikan partner mendidik anak. ingat ya, partner, jadi jangan lepas tangan.
2. Sekolah bukanlah semesta pendidikan. Sekolah hanya sebuah tempat. Sebuah rantai dari serangkaian upaya untuk mengajarkan anak melihat dunia. Jadi saya tidak bisa menganggap urusan pendidikan anak selesai dengan memberinya sekolah, tak peduli bagaimana rating sekolah itu. Bagus atau tidak sekolah, kami tetap masih harus mendidiknya di rumah.
3. Kadang-kadang saya pikir, urusan mencari sekolah yang baik ini, apakah benar-benar karena saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, atau karena saya tidak ingin mereka kalah dibandingkan anak-anak lain? Karena kalau saya benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak saya semata, maka seharusnya saya mengukur kredibilitas sekolah itu dari sudut pandang anak saya. Apakah itu tempat yang nyaman, apakah toiletnya tidak ketinggian, apakah guru itu tidak galak, apakah sekolah itu mengerti tentang beberapa keterbatasannya dan mengapresiasi dengan tulus beberapa kelebihannya?
4. Saya bertemu seorang ibu dari generasi di atas saya. Tinggal di desa, dengan sekolah negeri yang gaji gurunya pas-pasan, fasilitas terbatas, namun anak-anaknya berhasil tumbuh dewasa sebagai pribadi yang hebat? Dikasih apa Buuu?
"Sekolah itu tempat dia mendengar, melihat. Rumah itu tempat dia menyaring mana yang harus diterimanya, mana yang harus diabaikan."
Sang ibu menyediakan waktunya (sudah belasan tahun,kalau dihitung-hitung) untuk mendengarkan anak-anaknya. Obrolan seperti, tadi di sekolah belajar apa, temanmu kenapa, siapa yang terluka, siapa yang merusak apa, apa yang kalian lakukan ketika dihukum...
5. Tidak ada guru yang sempurna. Tentu saja, guru sesekali marah dengan yang berkecenderungan psikopat tentu berbeda. Saya mengenal seorang guru yang selalu mencaci-caci di wall facebooknya, memaki anak didiknya (meski di belakang) dan mengaku telah mematahkan penggaris di pantat muridnya. Saya berdoa cukup dia saja guru yang punya kelabilan jiwa seperti itu. Aamiin. Tapi, saya cukup tenang membaca nasihat Marie Hartwell--psikolog dan konsultan pendidikan untuk orang tua-- bahwa, guru bukanlah malaikat. Dia punya tekanan, masalah rumah, masalah sekolah, tuntutan orang tua dan kepala sekolah.. ketika suatu hari anda menemukan ia marah, jangan buru-buru memakinya balik dan mengeluarkan anak anda dari sekolah. Ajak ia bicara. siapa tau kepala dingin anda bisa menular padanya ;)
6. Dan, saya menemukan sekolah itu. TK negeri yang mungil, dengan halaman hijau dan pohon-pohon teduh. Ada banyak yang mengkritik, oke, bertanya, kenapa dan berapa. Bagi saya ini mencukupi. Semuanya bisa diatur, saya hanya perlu menginstal jiwa pembelajar dalam diri saya dan anak-anak. Kekurangan yang akan kami temui, akan kami bicarakan, akan kami perbaiki. Sebisanya. Kata seorang teman generasi tua: hadiahkan guru anakmu sebuah buku, atau sebuah obrolan dari hati ke hati....
Tentu saya khawatir pada efek kekerasan--apapun bentuknya-- termasuk tindakan bullying. Di negeri ini, drama komedi saja isinya mbully. Tapi, saya sendiri menghabiskan dua pertiga masa SD saya dengan menjadi korban bully sesama teman. Separo masa SMP saya dibully oleh guru. Masa SMU saya sepenuhnya dibully oleh sistem. Dan sebagian besar teman-teman saya merasakan hal yang sama. Kekerasan pada masa itu dianggap tindakan wajar, pendisiplinan. Tapi saya baik-baik saja, thank to my mother. Dan buku-buku serta kepercayaan diri yang diwariskan ayah saya.
Di masa ini, bukan berarti saya akan memaklumi tindak kekerasan di sekolah. Tapi saya akan kehilangan waktu dan banyak kesempatan jika hanya fokus menghindari. Kalaupun saya dan anak-anak bisa menghindari, tidakkah sebagai ibu cukup untuk membuat saya mempertimbangkan kecemasan ibu lain yang anaknya harus masuk ke sekolah negeri dengan banyak keterbatasan, sementara mereka tidak punya banyak pilihan. Saya mungkin bisa berlega untuk anak-anak saya, tp bagaimana dengan anak lain? Karena itu, saya memilih menerima ketidaksempurnaan, tidak menghindarinya mati-matian sampai kategori alergi sekolah miskin, dan bersama ibu-ibu lain, saya harap kami bisa memperbaikinya (cita-cita itu harus muluk, biar rajin mencapainya :))
Langganan:
Postingan (Atom)