 |
| Pictureperfectforyou.tumblr |
Ia seperti tak bisa diam. Ada saja yang membuat kaki dan tangannya bergerak. Menyapa ke sana ke mari, menyentuh ini itu, berlari, menendang, melompat, memukul, melempar... dan semuanya ia lakukan sambil tertawa atau berteriak. Tidak peduli 'korban'nya yang menangis.
Ia anak paling nakal di sekolah. Begitulah kata orang-orang. Jika seorang anak menangis, pastilah nama Afiz yang pertama diteriakkan. Pengasuhnya yang kurus tampak kwalahan mengejar dan mencegah bencana. Konon, beberapa anak sudah babak belur dibuat Afiz.
Setiap kali bertemu anak-anak, saya mematikan asumsi. Biarlah apa yang saya lihat sendiri yang berbicara. Pagi itu, sambil menemani Nizam bermain di ruang balita, saya melihat Afiz keluar dari kelasnya dan menghampiri kami.
"Halo," katanya dengan seringai lebar.
"Hai Afiz," kata saya. "Afiz tidak duduk di kelas?"
Dia menggeleng, masih menyeringai. Dalam satu gerakan cepat, ia merubuhkan jembatan balok Nizam. Dengan kakinya.
Nizam menatapnya kaget.
"Afiz akan membantu menyusun ulang," kata saya cepat, sebelum Nizam balas mengamuk.
Afiz mengangkat bahu, duduk di dekat saya dan mulai membantu Nizam menyusun kembali balok-balok itu. Saya kembali pada bacaan saya. Beberapa menit berselang, saya melihat keduanya sudah berhasil membangun jalan layang, menara, 'lumbung mobil busuk' dan sebagainya. Mereka tertawa bersama.
Di luar, saya lihat pengasuhnya mulai mencari ke mana Afiz.
Sebulan setelah kejadian itu, Afiz berulang kali keluar kelas dan bermain di kelas balita. Pengasuhnya cemas hal ini akan memengaruhi pembelajaran Afiz. Saya heran, apa sih yang diharapkan anak seusianya dipelajari selain bekerja sama dengan baik dan ketekunan dalam mengerjakan sesuatu? Bagi saya, dua hal itu jauh lebih penting daripada kemampuannya berhitung dan membaca, di usia ini. Tapi saya tidak punya hak mencampuri urusan pendidikan Afiz. Saya hanya bisa 'meracuni' pemikiran pengasuh dan gurunya, untuk membiarkannya bermain bersama kelas balita yang belum dicekoki calistung.
Suatu hari, kami di luar mendengar suara jeritan anak dari dalam kelas. Di kelas, guru sedang kesulitan memisahkan dua anak yang sedang berkelahi. Afiz dan seorang anak. Ibu-ibu yang sedan menunggu di luar berkata, "Anak itu memang nakal."
Tidak ada orang tua yang mau anaknya duduk di dekat Afiz.
Pengasuhnya tertunduk dengan rasa bersalah.
Siang itu saya mengawasi anak-anak bermain di dekat perosotan. Afiz dan Nizam bermain bersama. Dari tempat saya berdiri, saya melihat seorang anak menyikut Afiz. Afiz, yang cenderung cepat terpancing, berteriak dan mengejar anak itu. Untungnya ada yang segera memisahkan mereka.
"Afiz nakal!"
"Kenapa Afiz pukul?"
"Memang nakal. Dihukum saja."
Begitulah suara penonton.
Ia meronta-ronta di pelukan gurunya. Menangis begitu keras. Ketika akhirnya ia tidak mau masuk kelas dan memilih duduk di ayunan di luar, ia masih tersedu.
Tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang peduli untuk bertanya siapa yang memulai. Meski saya sendiri tidak pernah bertanya siapa di antara anak-anak yang lebih dulu memulai, setidaknya orang tua harus bersikap adil, tidak menyalahkan salah satunya. Keduanya berhak didengar. Keduanya berhak mendapatkan kesempatan untuk saling memaafkan, tanpa harus ada yang disebut di biang kerok atau si anak nakal.
Karena memang begitulah mereka berinteraksi. Menguji batas kesabaran satu sama lain. Menguji batas toleransi orang lain. Mencoba-coba apa yang membuat orang memerhatikannya. Mencari tahu mana yang boleh, mana yang berbahaya, mana yang tidak boleh tapi sebenarnya tidak apa-apa jika dilakukan.
Anak-anak adalah manusia yang masih cepat merasa bosan, ingin tahu banyak hal, ingin mencoba semua cara, tidak hanya cara biasa seperti yang ia lihat atau orang tua ajarkan. Itulah yang seringnya kita sebut nakal. Padahal, mereka hanya belajar tentang dunia dengan caranya sendiri.
Anak-anak yan dilabeli nakal, bodoh, bebal, liar, seperti kehilangan haknya untuk dipercayai. Seolah-olah ia tak lagi pantas didengar. Di mana ada suara tangisan, maka anak nakal itulah yang menjadi tertuduh sebagai penyebabnya.
Melihat Afiz yang menangis tersedu tanpa seorang pun yang memercayai bahwa ia tak salah, membuat hati saya ngilu. Sayang, saya bukan ibunya, pengasuhnya, gurunya, apalagi kepala sekolah. Saya hanya bisa mengeluarkan pesawat mainan dari tas Nizam,
"Kita masih punya waktu sepuluh menit, Ijam mau main sama Afiz? Pinjamkan dia ini,"
Putra kecil saya, yang sedari tadi memerhatikan Afiz, berlari memanggil temannya, dengan pesawat merah di tangan. "Kakak Apiiiz, ayo maiin..."
Andai saya bisa melakukan lebih. Andai saya bisa memeluknya dan berkata bahwa saya memercayainya.


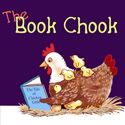








2 komentar:
tulisan yang sangat bagus mbak, dan penuh dengan pelajaran ^_^
Terkadang saya pun harus bersusah payah untuk tidak melabeli anak sendiri, karena saya tahu itu hanya akan menyakiti hatinya (apalagi kalo labelnya jelek)
Semoga kita semua sebagai orangtua bisa memahami hal ini ^_^
Terima kasih sudah mampir, Umm :) Benar, orang tua yng sudah faham pun terkadang keceplosan melabeli anak. Sungguh, selain berilmu, kita masih harus berusaha menjadi orang tua yg sabar...
Posting Komentar